Shalat merupakan ibadah pokok yang diwajibkan lima kali dalam sehari semalam bagi setiap muslim yang telah mencapai usia taklif (akil baligh). Ibadah ini memiliki kedudukan istimewa, sebab bagi siapa yang melaksanakannya akan diganjar pahala, sementara yang meninggalkannya akan menanggung dosa. Perintah shalat sendiri diterima langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ pada peristiwa Isra’ Mi‘raj tanpa perantara, sebagai bentuk kemuliaan sekaligus amanah agung bagi umat beliau.
Dalam konsep ushul fikih, suatu perintah pada
hakikatnya dimaksudkan agar orang yang diperintah benar-benar melaksanakan apa
yang diperintahkan. Dengan demikian, ketika Allah memerintahkan shalat, maka
maksud dari perintah itu adalah agar shalat dilaksanakan. Jika perintah
tersebut diabaikan dan tidak dikerjakan, maka tujuan perintah tidak tercapai
sehingga perintah itu seakan-akan tidak memiliki faedah. Dari sinilah kemudian
muncul sebuah pertanyaan penting: mengapa pelaku maksiat, khususnya orang yang
sama sekali tidak memiliki niat untuk menunaikan shalat, tetap diwajibkan untuk
melaksanakannya, padahal Allah Ta‘ala mengetahui bahwa ia tidak akan pernah
melakukannya?
Terkait persoalan ini, Syaikh Ahmad bin Abdul
Lathif al-Jawi dalam karyanya Hasyiah al-Nafahat ‘Ala Syarh al-Waraqat
memberikan komentar sebagai berikut:
فإن
قيل : لم طالب العاصي بالصلاة مع
أنه عالم بأنه لا يطيعه. قلنا : أحسن
ما قيل في جوابه أن الخطاب له ليس طلبا حقيقة بل علامة على شقاوته وتعذيبه أو
لتنقطع حجته عند الله والله الحجة البالغة لأن من عادته أنه لا يعذب حتى يرسل
إليهم رسولاً كما قال تعالى﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ أو لإظهار شقاوة من شقي بالمخالفة وسعادة من سعد بالمتابعة
“Jika ada yang
bertanya: Mengapa orang yang bermaksiat tetap dituntut untuk melaksanakan
shalat, padahal diketahui bahwa ia tidak akan menaatinya? Maka dijawab:
Penjelasan terbaik tentang hal ini adalah bahwa seruan (perintah) kepadanya
bukanlah perintah dalam arti hakiki, melainkan tanda kesengsaraannya dan bentuk siksaan
baginya. Atau agar terputus alasannya di hadapan Allah, karena Allah memiliki
hujjah yang sempurna; sebab kebiasaan-Nya, Dia tidak akan mengazab suatu kaum
sampai diutus kepada mereka seorang rasul, sebagaimana firman-Nya: “Dan
Kami tidak akan mengazab (suatu kaum) hingga Kami mengutus seorang rasul.”
(QS. Al-Isra’: 15). Atau juga agar tampak jelas kesengsaraan orang yang celaka
karena menolak perintah, dan kebahagiaan orang yang beruntung karena menaati
perintah”.
Berdasarkan
keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pelaku maksiat tetap
diperintahkan untuk melaksanakan shalat dapat dilihat dari beberapa sisi
berikut:
1. Perintah sebagai
tanda kesengsaraan (syaqawah)
Bagi orang yang
enggan menunaikan shalat, kewajiban tersebut menjadi tanda kesengsaraan
sekaligus bentuk siksa dari Allah. Ia diperintahkan untuk melaksanakan shalat,
namun dengan sengaja menolaknya, sehingga hal itu menjadi bukti nyata dari
kerugian atau kesengsaraan dirinya sendiri di hari akhirat kelak.
2. Menegakkan hujjah
Allah
Kewajiban shalat
juga berfungsi untuk memutus alasan manusia di hadapan Allah kelak. Tidak
seorang pun bisa berdalih bahwa ia tidak pernah diperintahkan untuk shalat,
karena perintah itu telah sampai kepadanya. Sesuai dengan sunnatullah, Allah
tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus kepada mereka seorang rasul.
Dengan demikian, kewajiban shalat merupakan bentuk ditegakkannya hujjah
sehingga azab Allah menjadi adil dan tidak terbantahkan.
3. Membedakan antara
yang taat dan yang ingkar
Perintah shalat
menjadi sarana ujian yang menyingkap hakikat hamba, yakni siapa yang celaka
karena menolak perintah Allah dan siapa yang berbahagia karena menaatinya.
Dengan begitu, perintah shalat berfungsi sebagai pembeda antara jalan ketaatan
dan jalan kesesatan.
Ref: Syaikh Ahmad bin Abdul Lathif al-Jawi, Hasyiah al-Nafahat ‘Ala Syarh al-Waraqat, Cet. Ke-2 (Beirut: DKI, 2013), h. 117.

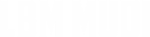








0 Komentar