Ketahuilah bahwa setiap orang yang telah dibebani kewajiban syariat
(mukallaf) seharusnya menjaga lisannya dari semua bentuk ucapan, kecuali
ucapan yang jelas mengandung maslahat. Dan apabila antara berbicara dan diam
itu seimbang dalam maslahatnya, maka sunnahnya adalah diam, karena ucapan yang
mubah bisa saja mengarah kepada yang haram atau makruh, bahkan
hal ini sering atau umumnya terjadi serta keselamatan
(dari keburukan lisan) tidak ada bandingannya dengan apa pun.
Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Barang
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik
atau diam”. (HR. Bukhari & Muslim). Di zaman
digital ini, kata-kata bisa tersebar lebih cepat dari cahaya. Ucapan lisan
berpindah menjadi status media sosial, komentar, atau pesan instan yang bisa
menyentuh ribuan orang hanya dengan satu klik. Tapi seberapa sering kita
berpikir dua kali sebelum berbicara atau sebelum mengetik?
Dalam Islam, menjaga lisan bukan sekadar etika sosial, tapi bagian
dari iman. Rasulullah ﷺ menjadikan lisan
sebagai barometer keimanan dan keselamatan akhirat. Maka, sudah saatnya kita
menengok kembali warisan ajaran Islam tentang pentingnya menahan kata, berkata
yang baik, dan diam bila perlu. Lisan Selalu dalam Pengawasan Ilahi
Allah
Ta’ala berfirman:
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ
“Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya
malaikat pengawas yang selalu hadir”. (QS. Qaf: 18).
Ayat ini menjadi pengingat bahwa tidak ada ucapan yang luput dari
catatan. Bahkan dalam ayat lain, Allah mengingatkan:
اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِۗ
“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.
(QS. Al-Fajr: 14).
Apa pun yang kita ucapkan, disengaja atau tidak, akan tercatat.
Maka berhati-hatilah karena lisan bukan hanya bagian dari diri, tapi juga
bagian dari hisab kelak di akhirat.
Berkata
Baik atau Diam: Saring Sebelum Sharing
Hadis dari Abu Hurairah ra. menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau
diam”. (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menyatakan bahwa berkata baik bukan hanya sekadar
adab, tapi indikator keimanan. Jika ucapan kita tidak mendatangkan manfaat
apalagi bisa menyakiti maka diam adalah pilihan paling selamat.
Imam Syafi’i rahimahullah bahkan berkata: “Jika seseorang hendak
berbicara, hendaklah ia berpikir. Bila tampak maslahatnya, barulah ia
berbicara. Jika ragu, lebih baik diam sampai jelas manfaatnya.”
Betapa banyak dari kita yang menyesal karena perkataan yang sudah
terlanjur keluar. Dalam satu hadis yang menggugah, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya
seorang hamba bisa mengucapkan satu kata tanpa memikirkannya, dan karenanya ia
tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat”.
(HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain, Nabi ﷺ
ditanya: Siapa muslim terbaik?, Beliau menjawab: “Yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya”.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Coba kita renungkan seberapa aman orang lain dari ucapan kita?
Apakah kita mudah bergunjing, menyindir, atau menyakiti orang lain lewat
kata-kata, baik langsung maupun di dunia maya?. Kita
hidup di masa di mana setiap orang bisa jadi “penyiar.” Tapi tidak semua orang
jadi penyampai kebaikan. Ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah digital tumbuh
subur padahal Islam justru meminta kita
menahan diri, bahkan dari ucapan yang sekadar “netral” jika tidak ada
manfaatnya. Sebagian orang merasa aman berkata apa saja karena “hanya
bercanda,” atau “hanya menyalurkan pendapat.” Tapi Rasulullah ﷺ sudah mengingatkan bahwa: “Siapa yang
menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya (lisan), dan apa yang ada
di antara kedua pahanya (kemaluan), maka aku jamin ia masuk surga”. (HR.
Bukhari).
Islam tidak
melarang bicara, bahkan banyak ucapan yang berpahala: zikir, nasihat, ilmu, atau
kata-kata lembut pada sesama. Tapi selebihnya, kita diminta waspada. Tidak
semua yang bisa diucapkan perlu diucapkan. Jaga lisan karena ia bisa menjadi jalan ke surga, atau
jerat ke neraka.
Referensi: Yahya bin
Syaraf an-Nawawi, al-Adzkar (Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. ke-1, 1425
H/2004 M), h.528-530.

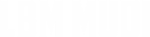








0 Komentar