Shalat merupakan
salah satu rukun Islam sekaligus ibadah badaniyah yang paling agung
dibandingkan dengan ibadah badaniyah lainnya, seperti puasa dan haji. Keagungan
shalat terletak pada keterpaduannya yang mencakup seluruh aspek ibadah: gerakan
tubuh, ucapan lisan, dan penghayatan hati. Shalat diwajibkan kepada umat Islam
pada peristiwa Isra’ Mi‘raj, setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad ﷺ ke Madinah.
Shalat juga memiliki syarat dan rukun tertentu, salah satu syarat sahnya adalah
menghadap kiblat. Pada mulanya, kiblat yang diperintahkan adalah Baitul Maqdis.
Namun, setelah kurang lebih enam belas hingga tujuh belas bulan, Allah ﷻ
memerintahkan pemalingan arah kiblat menuju Ka‘bah di Masjidil Haram.
Sebelum pemalingan arah kiblat, Rasulullah ﷺ
sebenarnya telah lama menginginkan agar shalat diarahkan ke Ka‘bah.
Diriwayatkan bahwa setelah menunaikan shalat, beliau sering menengadahkan
pandangan ke langit, menanti turunnya perintah Allah untuk mengalihkan kiblat.
Hingga akhirnya, Allah ﷻ menurunkan ayat yang memerintahkan pemalingan arah
kiblat menuju Ka‘bah, sesuai dengan apa yang beliau dambakan. Yaitu sebagai berikut:
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) ١٤٤(
“Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu (Muhammad) menengadah ke langit,
maka sungguh akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah
wajahmu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi Kitab (Yahudi
dan Nasrani) benar-benar mengetahui bahwa (pemalingan kiblat itu) adalah
kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka
kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 144)
Nah, di sini terdapat persoalan menarik untuk
dikaji: mengapa Rasulullah ﷺ begitu menginginkan pemalingan arah kiblat dari
Baitul Maqdis ke Ka‘bah, padahal saat itu Allah memerintahkan beliau untuk
menghadap ke Baitul Maqdis?. Sedangkan secara prinsipnya, setiap perintah Allah
seharusnya diterima dengan penuh kerelaan bahkan disertai kecintaan. Karena
itu, tidaklah dibenarkan untuk berdoa atau meminta perubahan terhadap
hukum-hukum yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah ﷻ.
Terkait persoalan ini, Ibn Hajar al-Haitami dalam karyanya Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra mengemukakan alasan Rasulullah ﷺ menginginkan pemalingan arah kiblat, yaitu bahwa keinginan tersebut memiliki dasar maslahat yang besar. Hal ini dengan beberapa alasan:
1. Ka‘bah adalah kiblat Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya. Selain itu, bangsa Arab sangat mengagungkannya, sehingga dengan pemalingan arah kiblat, Rasulullah ﷺ berharap mereka akan lebih mudah menerima Islam. Hal ini penting, sebab jumlah bangsa Arab pada waktu itu lebih banyak dibandingkan Bani Israil
2. Masa diwajibkan menghadap ka’bah lebih panjang dari pada masa diwajibkan menghadap baitul maqdis dan Ka‘bah juga berfungsi sebagai nasikh (penghapus) terhadap kewajiban sebelumnya, sehingga shalat menghadap Ka‘bah lebih utama dibandingkan menghadap Baitul Maqdis.
Selanjutnya, Ibn
Hajar menegaskan bahwa kerelaan terhadap perintah Allah tidak bertentangan
dengan adanya permohonan untuk meraih sesuatu yang lebih utama dalam rangka
mendekatkan diri kepada-Nya. Larangan meminta perubahan hukum hanya berlaku setelah
wafat Nabi ﷺ, ketika kemungkinan adanya nasakh (penghapusan hukum) sudah
tidak ada lagi. Adapun pada masa beliau masih hidup, perubahan tersebut masih
dimungkinkan karena wahyu terus turun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
keinginan Rasulullah ﷺ agar kiblat dipalingkan ke Ka‘bah bukanlah bentuk
ketidakridhaan terhadap perintah Allah, melainkan sebuah upaya yang didasari
harapan untuk meraih maslahat yang lebih besar serta pendekatan diri yang lebih
sempurna kepada Allah ﷻ.
Refrensi:
1. Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, Tafsir al-Qurṭubī, Jld. 2, Cet. Ke-2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 158.
2. Ibn Hajar al-Haitami, Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, Jld. 1, (Maktabah Islamiyyah), h. 137.

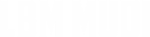








0 Komentar