Dalam literatur fikih, istilah hukum didefinisikan sebagai ketentuan syariat Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Adapun dalam ushul fiqh pengertian hukum adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan. Lebih jelasnya bisa dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasulullah saw., yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun hubungan antar manusia (muamalah) dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.
Dalam perspektif ini, sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadis, kemudian diikuti oleh sumber turunan seperti ijma’ (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum).
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., yang menjadi mukjizat dengan surahnya.[2] Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang kepada Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Maidah Ayat 44-45, dan 47:
ذلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Al-Baqarah: 2).
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ اْلكفِرُوْنَ
Artinya: “Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang kafir”. (Al-Maidah: 44).
Tentu dalam hal ini yang bersangkutan dengan aqidah, lalu:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون
Artinya: “Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang zalim”. (Al-Maidah: 45).
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
Artinya: “Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah golongan orang-orang fasik”. (Al-Maidah: 47).
2. Sunnah (Hadis)
Sumber kedua dalam menentukan hukum syariat ialah Hadis Rasulullah ٍsaw.. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (diamnya beliau terhadap suatu perbuatan), maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun akhlak. Maka karena demikian wajib bagi kita mengikuti dan berpegang dengan Hadis, sebab adanya perintah Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 92, An-Nisa` ayat 80 dan Al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْاۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ
Artinya: “Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (ajaran Allah) dengan jelas”. (Al-Maidah: 92).
مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًاۗ
Artinya: “Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka”. (An-Nisa`: 80).
وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ
Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras sikapnya”. (Al-Hasyr: 7).
Ketiga ayat tersebut disebutkan oleh Al-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki dalam kitabnya al-Minhal al-Lathif. Sebagai tambahan beliau juga menyebutkankan surah Al-Ahzab ayat 21 dan Ali-‘Imran ayat 31, semua ayat tersebut merupakan hujjah Hadis sebagai sumber hukum syariat. Rasulullah saw. Bersabda:
تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهِ
Artinya: Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara, selama-lamanya tidak akan tersesat jika kamu sekalian senantiasa berpegang kepada keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Malik)[3]
3. Ijma’
Yang disebut ijma’ ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw., seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid. Kemudian ijma’ ada dua macam, yaitu:
1) Ijma’ bayani (الاجماع البياني) ialah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukan kesepakatannya.
2) Ijma’ sukuti (الاجماع السكوتي) ialah apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukan setuju, bukan karena takut atau malu. Dalam ijma’ sukuti ini ulama masih berselisih paham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan.
Adapun ijma’ bayani telah disepakati suatu hukum, wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan mentaati. Karena para ulama mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Qur’an dan Hadis. Diketahui para sahabat pernah melaksanakan ijma’ apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadis. Rasulullah saw. pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Inilah beberapa Hadis yang memperkuat Ijma’ sebagai sumber hukum, seperti yang disebutkan dalam al-Mustashfā min ‘Ilm al-Ushūl:
لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة و سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها
Artinya: “Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan, dan Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Aku pun memohon kepada Allah Ta’ala agar tidak menjadikan umatku berkumpul di atas kesesatan, maka Allah mengabulkan permintaanku”.[4]
Selanjutnya, dalam kitab Sunan Ibnu majah disebutkan:
إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ
Artinya: “Sesungguhnya umatku tidak berkumpul atas kesesatan maka apabila engkau melihat perselisihan, maka hendaknya engkau berpihak kepada golongan yang terbanyak”.[5]
4. Qiyas
Qiyas menurut bahasa berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa (قاس). Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Rukun Qiyas ada empat yaitu: al-Ashlu, al-far’u, al-hukmu dan al-sabab. Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokok (al-ashlu)-nya, lalu al-far’u-nya adalah beras (tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis), al-hukmu atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sabab atau alasan hukumnya karena makanan pokok. Dengan demikian, hasil gandum itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis Nabi, dan begitupun dengan beras, wajib dikeluarkan zakat. Meskipun, dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Tetapi, karena beras dan gandum itu kedua-duanya sebagai makanan pokok. Di sinilah aspek qiyas menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur’an Allah Swt. berfirman: فَاعْتَبِرُوْا يأُوْلِى اْلأَيْصَار “Ambilah ibarat (pelajaran dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan”. (Al-Hasyr:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِي وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ فِيمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin ‘Umar, dari Syu’bah, dari Abu ‘Aun, dari al-Harits bin ‘Amru bin Akhi al-Mughirah bin Syu‘bah, dari sejumlah orang penduduk Hims dari sahabat-sahabat Mu‘adz bin Jabal: Bahwa ketika Rasulullah saw. hendak mengutus Mu‘adz ke Yaman, beliau bertanya, Bagaimana engkau akan memutuskan perkara jika ada suatu urusan (perkara hukum) yang diajukan kepadamu? Mu‘adz menjawab, Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah (Al-Qur’an). Beliau bertanya lagi, Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitab Allah? Mu‘adz menjawab, Maka dengan Sunnah Rasulullah saw. Beliau bertanya, Jika engkau tidak menemukannya dalam Sunnah Rasulullah dan tidak (pula) dalam Kitab Allah? Mu‘adz menjawab, Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyia-nyiakan (usaha untuk mencari kebenaran). Maka Rasulullah saw. menepuk dadaku seraya bersabda “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang diridhai Rasulullah”.[6]
Kemudian Imam al-Syāfi’i memperkuat pula tentang qiyas dengan firman Allah swt. dalam Al-Qur’an:
ياأَيُّهَا اَّلذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَتَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram, barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu”. (Al-Maidah: 95).
Dari penjelasan mengenai Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, dapat disimpulkan bahwa keempatnya merupakan fondasi pokok dalam penetapan hukum syariat. Keempatnya saling melengkapi sehingga membentuk aturan yang kuat, jelas, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Allah Swt.
Referensi:
Muhammad bin ‘Afifi al-Khudhari Bik, “Ushul al-Fiqh”, (Kairo: “Dār al-Hadīts al-Qāhirah, 2003), hal. 21.
Al-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki, “al-Qawa’id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran”, (Surabaya: Hai’ah al-Shafwah al-malikiyyah, tt), hal. 9.
Al-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki, “al-Minhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif (Surabaya: Hai’ah al-Shafwah al-malikiyyah, tt), hal. 11.
Al-Imām Abī hāmid ibn Muhammad al-Ghazālī, al-Mustashfā min ‘Ilm al-Ushūl, Cet.1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), h. 221.
Al-Hāfizh Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn yazīd al-Qazwīnī, “Sunan Ibnu mājah”, Jld. 2, Cet. 1, (Kairo: Mathba’ah Dār Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1952), h.1303.
Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbās Ahmad ibn Husain ibn ‘Alī ibn Ruslān, “Syarh Sunan Abī Dāwud”, Juz. 14, Cet. 1, (Kairo: Dār al-Falāh li al-Bahts al-‘Ilmiyyi wa Tahqīq al-Turats, 2015), h. 646 – 650.

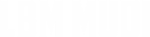







0 Komentar